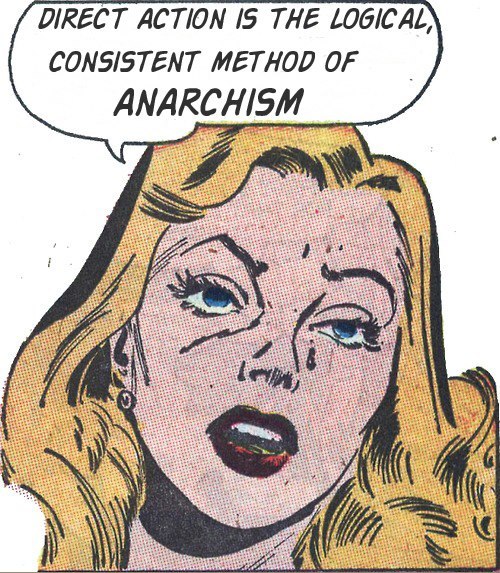(Half Face)
Jumat, 25 Januari 2013
Film Review
Hotel Rwanda :
Konstruksi Kolonial, Revolusi, dan
Genoside
 Hotel Rwanda,
merupakan sebuah film besutan sutradara Terry George, yang
mengambil setting pada kejadian kejahatan genosida di Rwanda pada tahun 1994.
Film ini mengisahkan kejadian nyata akan kejahatan genosida di Rwanda dari
sudut pandang seorang manajer hotel bernama Paul Rusesabagina
(diperankan Don Cheadle), seorang manajer hotel Sabena
Hôtel des Mille Collines, adalah seorang Hutu namun istrinya, Tatiana (diperankan
oleh Sophie Okonedo), adalah seorang Tutsi. Pernikahannya menjadikannya penghianat
bagi ekstrimis Hutu yakni George Rutaganda, seorang kenalan baik dan penyalur
kebutuhan hotel yang juga merupakan pemimpin dari Interahamwe, milisi Hutu yang
anti Tutsi.
Hotel Rwanda,
merupakan sebuah film besutan sutradara Terry George, yang
mengambil setting pada kejadian kejahatan genosida di Rwanda pada tahun 1994.
Film ini mengisahkan kejadian nyata akan kejahatan genosida di Rwanda dari
sudut pandang seorang manajer hotel bernama Paul Rusesabagina
(diperankan Don Cheadle), seorang manajer hotel Sabena
Hôtel des Mille Collines, adalah seorang Hutu namun istrinya, Tatiana (diperankan
oleh Sophie Okonedo), adalah seorang Tutsi. Pernikahannya menjadikannya penghianat
bagi ekstrimis Hutu yakni George Rutaganda, seorang kenalan baik dan penyalur
kebutuhan hotel yang juga merupakan pemimpin dari Interahamwe, milisi Hutu yang
anti Tutsi.
Dalam film
ini diceritakan kemudian pada malam pembantaian, tetangga-tetangga dan keluarga
Paul baik dari suku Hutu maupun Tutsi sangat berharap padanya supaya dapat ia
selamatkan. Kemampuan negosiasi dan kepemimpinan yang dilakukan oleh paul,
membuatnya dapat menyelamatkan keluarga dan tetangganya dari milisi Hutu
bersenjata yang bertujuan menghabisi semua suku Tutsi. Setelah tawar menawar
dengan seorang petugas militer Rwanda untuk keselamatan keluarga dan teman,
Paul membawa mereka ke hotelnya. Setelah dapat menyelamatkan keluarga dan
tetangganya, berita tersebut banyak tersebar sehingga semakin banyak orang yang
menjadi pengungsi yang kemudian membanjiri hotelnya. Pihak PBB tidak dapat
berdaya, dikarenakan kamp pengungsian PBB sangat berbahaya dan terlalu penuh
pada saat itu.
Tentara
Bizimungu akhirnya dapat mengakhiri
kekacauan dan Paul panik mulai mencari istri dan keluarganya, berpikir kalau
mereka sudah bunuh diri seperti yang diperintahkan Paul apabila orang-orang
Hutu dapat menyerang hotel. Setelah ketakutan setengah mati, Paul menemukan
mereka bersembunyi di kamar mandi. Keluarga dan para pengungsi akhirnya dapat
keluar dari hotel dengan kawalan konvoi pasukan PBB. Mereka menempuh perjalanan
melewati pengungsi Hutu dan milisi Interhamwe menuju ke belakang garis depan
pihak pemberontak Tutsi. Di akhir cerita, dengan bantuan dari Madame Archer Paul
menemukan kedua keponakannya yg masih kecil, yang keberadaan orang tuanya tidak
diketahui, dan mengajak mereka dengan keluarganya keluar dari Rwanda.
Salah
satu penyebab mendasar dari genosida yang terjadi di Rwanda tahun 1994
merupakan konflik yang terjadi antara 2 suku besar di Rwanda yakni Konflik
antara suku Hutu dan Tutsi. Jika dilihat sekilas hampir tak ada perbedaan dalam
warna kulit, bentuk tubuh maupun ukuran yang dimiliki oleh suku-suku tersebut.
tapi pada waktu penjajahan Belgia, suku Hutu di anggap sebagai suku yang
minoritas sedangkan Tutsi dianggap sebagai suku yang lebih tinggi
eksistensinya.
Hal tersebut
karena suku Tutsi memiliki warna kulit yang lebih terang, postur tubuh yang
tinggi, langsing dan juga memiliki ukuran hidung yang lebih ramping dan mancung[1].
Sedangkan suku Hutu memiliki kulit yang berwarna lebih hitam, postur yang agak
pendek, hidungnya besar dan pesek. Para penjajah Belgia lebih memilih
orang-orang dari suku Tutsi untuk menjalankan pemerintahan daripada orang-orang
yang berasal dari suku Hutu. Mereka mempekerjakan suku Tutsi untuk pekerjaan
“kerah putih” yaitu pekerjaan yang lebih tinggi posisinya misalnya menjadi
petugas administrasi .
Sedangkan
untuk “kerah biru” yaitu posisi yang lebih rendah, dan pekeja kasar diberikan
kepada suku Hutu yang sebenarnya merupakan penduduk mayoritas di Rwanda. Secara
tidak langsung, Belgia selaku pihak kolonial menkonstruksi perbedaan-perbedaan
besar tak berdasar yang digunakan mengadu domba ke 2 suku ini. Konstruksi kolonial yang membagi mana suku
yang lebih tinggi derajatnya mana yang lebih rendah menyebabkan kebencian yang
mengakar khususnya bagi suku Hutu yang dianggap lebih rendah. Hal itu, kemudian
dibalas oleh suku Hutu dengan justifikasi diri sebagai yang “dominan” ketika
Rwanda sudah merdeka.
Klasifikasi
“dominan-minoritas” inilah yang saya lihat sebagai salah satu aspek yang
menambah kebencian Hutu kepada Tutsi, bahwa orang-orang Tutsi adalah minoritas
pendatang yang juga merupakan penghianat, mereka dianggap tidak lebih dari “Cocoroaches”[2].
Proses dehumanisasi ini sangat terlihat disini, orang-orang Tutsi sudah
dianggap tidak lebih dari hewan, yakni kecoa.
Penghapusan perbedaan yang
berada di masyarakat Rwanda,
merupakan sebuah gambaran mengenai modernitas yang juga dipaparkan oleh A.L. Hinton (2002) dalam
bukunya “The Dark Side of Modernity: Toward an.
Anthropology of Genocide.
[1]Hal ini
ada dalam dialog ketika wartawan asing sedang berbincang di hotel dan
menanyakan perbedaan antara suku hutu dan tutsi. Pembentukan konstruksi sosial
oleh kolonial inipun ada pada buku “The Specther Of Genocide” hal 326-330
[2] Dalam
film Hotel Rwanda, beberapa kali milisi Interahamwe dan pemimpinnya Rutaganda menyebut suku tutsi sebagai
“Cocoroaches” atau kecoa.
Book Review
Ritual
Process
Victor
Turner
Pada tulisan dan buku ini Turner,
dalam bab satu, membahas dengan sangat lengkap mengenai Isoma. Ritual Isoma
atau lebih dikenal dengan ‘ritual perempuan’, merupakan subkelas dari ritual
yang dikaitkan dengan roh para leluhur. Istilah khusus ritual bagi Ndembu
adalah chidika atau perjanjian
khusus. Ritual sendiri dilakukan manakala seseorang atau kelompok usaha gagal
memenuhi kewajiban mereka. Ritual Isoma sendiri dilakukan karena
ketidakberuntungan yang dialami oleh perempuan terkait dengan kapasitas
reproduksi dirinya. Orang Ndembu mempratikkan model kekerabatan matrilineal di
satu sisi, dan mempraktikkan model virilokal di sisi lainnya. Kondisi ini
menyebabkan seorang perempuan Ndembu yang menikah terjerat dalam arena
kontestasi antara suami dan saudara laki-laki dari pihak ibu. Dalam kondisi
lain, seorang perempuan yang menikah dan melahirkan, dalam jangka pendek atau
panjang, akan membawa anak yang dilahirkannya untuk masuk dan berafiliasi dalam
klan ibu (matrilineal).
Konsekuensi lain dari model ini
adalah bahwa masyarakat Ndembu mendasarkan keberlangsungan hidup mereka dari
ketidakberlanjutan hubungan perkawinan. Hal ini disebabkan bahwa perempuan yang
bercerai akan kembali ke kerabatnya dan membawa anak yang dilahirkannya.
Berbeda halnya jika seorang perempuan menikah dan memiliki anak, dan bertempat
tinggal bersama suaminya, namun tidak kembali ke kerabatnya, maka perempuan
tersebut dianggap tidak memenuhi “tugasnya” untuk menjaga keberlangsungan
kerabatnya. Seorang perempuan diharapkan berpartisipasi dalam menjaga
keberlangsungan kerabatnya dengan menyumbangkan kemampuan fertilitas yang dia
miliki agar dia tetap memiliki hubungan dengan para leluhurnya. Kegagalan dalam
pemenuhan tugas ini menjadikan mereka sebagai orang yang “melupakan” asal-usul
dan tujuannya, dan ritual Isoma memiliki peran khusus untuk mengingatkan
kembali di mana harusnya dia meletakkan loyalitasnya. Isoma juga berlangsung
jika seorang perempuan memiliki “kegagalan” dalam reproduksi, baik itu
melahirkan anak atau pun merawat kehamilan. Ritual ini dipimpin oleh seorang
dokter atau chimbuki yang dianggap
mengetahui mengenai pengobatan. Di sisi yang berbeda, setiap ritual yang
dilakukan oleh Ndembu selalu melibatkan seperangkat simbol. Bagi Turner, orang
Ndembu sangat menyadari fungsi ekspresif dari simbol dalam setiap ritual
mereka, termasuk dalam Isoma. Pelaksanaan Isoma secara implisit memiliki tujuan
untuk merestorasi hak dalam hubungan antara kekerabatan matrilineal dan
perkawinan, merekonstruksi hubungan perkawinan antara suami dan istri, dan
membuat hubungan antara perempuan, kekerabatannya dan perkawinannya, berhasil.
Dalam istilah Ndembu, ritual ini membuang chisaku
atau ketidakberuntungan atau penyakit yang ditimbulkan akibat membuat leluhur
tidak senang atau melanggar tabu .
Jika pada bab satu Turner
menjelaskan dengan sangat lengkap mengenai Isoma, maka pada bab selanjutnya
Turner mencoba menjelaskan kontradiksi pada anak kembar. Turner mencoba
menjelaskan mengenai Wubwang’u.
Ritual ini dilaksanakan untuk menguatkan perempuan yang dianggap akan memiliki
dua anak kembar atau jika si anak tersebut telah lahir atau ampamba. Keberadaan anak kembar memang
paradoks. Paradoks ini muncul manakala keberadaan anak kembar dilihat dalam
pandangan orang Ndembu. Sebagaimana digambarkan sebelumnya, orang Ndembu
memberikan porsi yang utama pada masalah fertilitas, di mana kita melihat
keterkaitan antara fertilitas dengan fisiologi dengan kesulitan ekonomi.
Dalam pandangan Turner, dalam
masyarakat yang tidak berternak atau tidak memiliki gagasan bahwa biri-biri dan
kambing dapat diambil susunya untuk konsumsi, maka akan sangat sulit bagi
seorang perempuan untuk memiliki dua anak dan menyusui anak-anaknya. Seringkali
keberlangsungan hidup anak tersebut bergantung pada belas kasihan orang lain, misalnya
perempuan yang anaknya meninggal dan ia masih memiliki persediaan air susu. Di
sisi yang berbeda, ritual wubwang’u
memiliki paradoks lain dalam keteraturan struktur sosial. Turner mengutip
Schapera, yang menggambarkan fakta bahwa di mana pun kekerabatan secara
struktural memegang posisi yang signifikan, terlebih jika menghasilkan kerangka
hubungan korporasi dan status sosial, kelahiran anak kembar adalah sesuatu yang
memalukan. Hal ini disebabkan adanya asumsi dasar bahwa manusia melahirkan
hanya satu anak dalam satu waktu, dan hanya satu tempat yang tersedia dalam
struktur sosial di mana anak tersebut dilahirkan. Hubungan saudara kandung
adalah faktor penting lainnya. Dalam suatu struktur sosial, keberadaan kakak
seringkali memiliki hak lebih ketimbang adik-adiknya, dan hal ini menjadi
persoalan ketika lahir anak kembar, di mana secara fisik terdapat dua individu
namun secara struktural hanya ada satu posisi yang disediakan, dan apa yang
mistis satu namun secara empiris dua. Ritual wubwang’u sebagaimana ritual-ritual lainnya, memegang posisi
penting bagi diri perempuan. Ritual ini dilaksanakan bagi perempuan yang
melahirkan anak kembar atau perempuan yang dianggap (atau diharapkan) memiliki
anak kembar. Selanjutnya pada bagian tiga dari tulisan Turner. Berbeda dengan
dua tulisan berikutnya yang secara detail membahas dengan sangat mendetail
mengenai ritual dalam masyarakat Ndembu, bagian tiga (dan sisa bab lainnya)
membahas aspek struktural yang dikaitkan dengan dua bab berikutnya. Secara
khusus bab ini membahas mengenai liminalitas dan komunitas. Terus terang, tidak
mudah menjelaskan perbedaan penerjemahan antara communitas dengan community,
keduanya diterjemahkan sebagai ‘’komunitas’’ dalam bahasa Indonesia.
Meskipun demikian, Turner membedakan
antara kommunitas dan kommuniti, dalam pandangan Turner, jika saya tidak salah
dalam memahami, community merujuk pada sebuah wilayah yang ditempati oleh
masyarakat, dalam hal ini community adalah sebuah teritori. Maka dengan itu,
saya tidak memaksudkan dengan menulis komunitas yang merujuk pada community,
namun komunitas di sini merujuk pada communitas yang digunakan oleh Turner. Liminalitas,
merupakan konsep yang dipinjam dari van Gennep, secara sederhana dipergunakan
untuk merujuk pada ritus peralihan atau rites
de passage. Ritus peralihan sendiri terjadi untuk menandai sebuah perubahan
atau peralihan tempat, keadaan, kedudukan sosial dan usia. Pelaksanaan ritus
peralihan dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu separasi (separation) atau
pemisahan, margina atau peminggiran, dan agregasi. Pemisahan ditandai dengan
terbentuknya perilaku simbolik yang menjadi penanda adanya keterpisahan
individu (atau kelompok) dari posisi awalnya dalam struktur sosial. Margin
adalah posisi antara, di mana individu (atau kelompok) tersebut belum dapat
sepenuhnya melepaskan atributnya, sekaligus belum dapat sepenuhnya mencapai
atributnya yang baru. Sedangkan agregasi ditandai dengan pembentukan kembali
melalui pemberian atribut setelah proses pengukuhannya selesai
Book Review
The Rules of Sociological Method
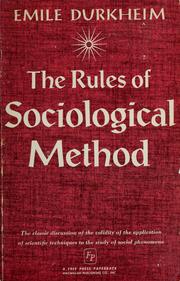 Buku
The Rules of Sociological Method,
merupakan buku yang dihasilkan dari tangan salah seorang “maestro” ilmu sosial,
yakni E.Durkheim. Dalam bukunya, Durkheim banyak membahas mengenai pentingnya
fakta sosial dalam mengetahu berbagai macam fenomena sosial dan juga buku ini
juga menjelaskan mengenai proses sosiologi menjadi ilmu di ranah empiris
melalui berbagai macam metode dan analogi ilmu eksakta. Dalam pembahasannya,
Durkheim membahas secara mendetail dengan membaginya kedalam 6 sub bab bahasan,
antara lain : hakikat fakta sosial, aturan mengenai observasi fakta sosial,
aturan mengenai pembedaan antara normal dengan abnormal (patologis),
klasifikasi tipe sosial, penjelasan mendalam, mengenai fakta sosial, dan aturan
untuk mendirikan pembuktian sosiologis.
Buku
The Rules of Sociological Method,
merupakan buku yang dihasilkan dari tangan salah seorang “maestro” ilmu sosial,
yakni E.Durkheim. Dalam bukunya, Durkheim banyak membahas mengenai pentingnya
fakta sosial dalam mengetahu berbagai macam fenomena sosial dan juga buku ini
juga menjelaskan mengenai proses sosiologi menjadi ilmu di ranah empiris
melalui berbagai macam metode dan analogi ilmu eksakta. Dalam pembahasannya,
Durkheim membahas secara mendetail dengan membaginya kedalam 6 sub bab bahasan,
antara lain : hakikat fakta sosial, aturan mengenai observasi fakta sosial,
aturan mengenai pembedaan antara normal dengan abnormal (patologis),
klasifikasi tipe sosial, penjelasan mendalam, mengenai fakta sosial, dan aturan
untuk mendirikan pembuktian sosiologis.
Pada
pembahasan Fakta sosial, Durkheim mengatakan hal yang mengikat individu dan di
luar individu, tidak bisa dibantah, dan biasanya merupakan proses imitasi, adanya
penyebaran atau difusi cara bertindak. Fakta sosial juga merupakan kesadaran
kolektif (l’amme collective), yaitu
bentukan dari segala macam peleburan state
pada individu-individu. Apabila fakta sosial koheren dengan kemauan individu
(individual manifestation/own right independent) maka hal ini disebut dengan
fakta psikologis. Lalu, apabila kita hanya membicarakan tentang
peraturan-peraturan (nilai dan norma) yang mengekang kolektif tersebut maka disebut
dengan fakta psikologis.
Pembahsan
kedua yakni mengenai obeservasi sosial, pada bab ini dibahas mengenai beberapa
persoalan. Pertama, dibahas mengenai bagaimana sosiologi itu sendiri bertindak
sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Sosiologi disini juga dibahas sebagai suatu
ilmu yang bebas nilai. Dan keharusan sosiologi sebagai suatu ilmu untuk
memiliki tujuan, yakni sebagai alat untuk menelaah fakta-fakta sosial.
Pembahasan
ketiga, yakni mengenai membedakan sesuatui
yang dianggap normal dengan sesuatu yang dianggap tidak normal dan patologis.
Maksud dari sesuatu hal dianggap normal adalah sesuatu yang disetujui secara
kolektif, sedangkan hal yang dianggap tidak normal adalah segala sesuatu yang
dianggap tidak sesuai dengan keinginan kolektif. Namun yang perlu menjadi
perhatian seperti yang tercantum dalam pembahasan bab ini yakni mengenai
keharusan jua untuk melihat konteks sosial juga yang ada untuk dapat memutuskan
hal-hal yang normal atau abnormal tersebut.
Pembahasan
keempat, yang dibahas di bab selanjutnya membahas mengenai bagaimana caranya
melakukan sebuah klasifikasi sosial. Ada dua sifat dari klasifikasi, yaitu
klasifikasi yang rigid atau kaku
serta klasifikasi yang bercampur. Lalu, hasil dari klasifikasi ini ada dua,
yaitu social morphology dan social evolution. Klasifikasi yang
pertama menunjukan didalam masyarakat adanya solidaritas, kerja sama, dan
hubungannya yang baik dengan alam sedangkan klasifikasi yang kedua menunjukan
dalam masyarakat adanya yang ditengarai sebagai
kerja sama kontraktual, dan hubungannya yang relatif terhadap alam.
Pembahasan
kelima, yakni dibahas mengenai bagaimana caranya menjelaskan fakta sosial.
Dijelaskan bahwa, fakta sosial merupakan
hal yang dapat dijelaskan melalui hubungan kausalitas atau sebab akibat. Fakta
sosial juga dijelaskan sebagai produk tambahan dari fakta psikologis
(kesadaran, sensasi, refleks, dan insting individu) tetapi tidak menjadikan
fakta psikologis sebagai acuan utama untuk menyelesaikan suatu fenomena sosial.
Ada pula alat ukur untuk menentukan fakta sosial, yaitu social millieu. Ada dua alat ukur, yaitu dynamic density serta physical
density. Pertama adalah seberapa besar takaran hubungan sosial dibandingkan
dengan kepentingan. Kedua adalah alat ukur numerik (pasti) dari perubahan
komunikasi. Alat ukur pastinya adalah seberapa besar dialog ataupun monolog
yang terjadi pada interaksi sosial tersebut.
Dan
hal keenam atau hal yang terakhir dibahas dalam buku ini yakni dibahas mengenai
bagaimana melakukan sebuah pembuktian secara sosiologis. Metode yang ditawarkan
adalah metode komparatif, yaitu membandingkan hubungan sebab dan akibat.
Hubungan yang terjadi haruslah terjadi secara dua arah, serta sebab atau akibat
yang ada harus lebih dari satu buah. Metode ini berasal dari pemikiran Comte tentang
metode historis yang menjadikan keteraturan sosial (teleologis) bertahap menjadi
tiga bagian, yaitu teologis, epistemologi, dan aksiologis. Lalu, metode lainnya
berasal dari Mill yang mengutip system of
logic, dan sebenarnya hal tersebut merupakan pengandaian ilmu ekonomi
sebagai ilmu praktis yang mempunyai tujuan tertentu. Metode dari Mill tersebut
menginspirasikan adanya hubungan kausal yang tidak hanya berasal dari sebab
pertama yang mengakibatkan sebab pertama. Metode kedua adalah metode asosiasi.
Metode ini merupakan metode perbandingan antar variabel yang terdapat pada
judul penelitian. Metode terakhir yakni mengenai metode deduktif. Metode
deduktif, adalah metode yang menitikberatkan kepada hal yang umum lalu kepada
hal yang khusus. Artinya, kita harus memakai teori dahulu serta hipotesis untuk
menduga secara baik, dan hasil akhirnya diukur melalui sebuah rangkaian uji
teori, dan konsep.
REFERENSI
:
Durkheim,
Emile. 1932. The Rules of Sociological
Method. Chicago: The University of Chicago Press.
Carok!!
Carok!!!
Masyarakat
Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik.
Penggunaan istilah khas menunjuk pada pengertian bahwa entitas etnik Madura
memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik
lain (Hasan Alwi, 2001: 563). Kekhususan kultural itu tampak antara lain pada
ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figur
utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis keberagamaan. Keempat figur
itu adalah Buppa,’ Babbu, Guru, dan
Rato (Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin pemerintahan). Kepada figur-figur
utama itulah kepatuhan hierarkis orang-orang Madura menampakkan wujudnya dalam
kehidupan sosial budaya mereka (Wiyata, 2003: 1).
Secara
hierarkis posisi kepatuhan masyarakat Madura dapat diurutkan sebagai berikut.
Yang pertama adalah kepatuhan terhadap ayah dan ibu (buppa dan babbu) kemudian
yang ketiga adalah kepatuhan terhadap guru atau ulama dan yang terakhir adalah
kepatuhan terhadap Rato atau pemimpin pemerintahan.
Kepatuhan
terhadap orang tua baik ayah dan ibu sudah sangat jelas dan telah diakui. Hal
tersebut juga berlaku tidak hanya pada etnis Madura melainkan berlaku juga terhadap
berbagai etnis lain yang ada. Dalam berbagai budaya yang ada hal tersebut sudah
menjadi hal yang mutlak. Kepatuhan seorang anak terhadap ayah dan ibunya
menjadi hal yang harus ditaati dan harus dilaksanakan. Perbedaan yang mungkin
terjadi adalah tata cara yang dilakukan dalam mengintepretasikannya. Selain itu
yang berbeda adalah cara-cara yang dilkukan untuk mewariskan nilai-nilai
kepatuhan tersebut. Secara siklus hal tersebut akan terus berjalan melalui
proses pewarisan.
Menurut
Taufiqqurrahman, kepatuhan orang-orang Madura kepada figur guru berposisi pada
level-hierarkis kedua. Penggunaan dan penyebutan istilah guru menunjuk dan
menekankan pada pengertian Kiai-pengasuh pondok pesantren atau
sekurang-kurangnya Ustadz pada “sekolah-sekolah” keagamaan. Peran dan fungsi
guru lebih ditekankan pada konteks moralitas yang dipertalikan dengan kehidupan
eskatologis ─ terutama dalam aspek ketenteraman dan penyelamatan diri dari
beban atau derita di alam kehidupan akhirat (morality and sacred world). Oleh karena itu, ketaatan
orang-orang Madura kepada figur guru menjadi penanda khas budaya mereka yang
mungkin tidak perlu diragukan lagi keabsahannya.
Siklus-generatif
tentang kepatuhan orang Madura (sebagai murid) kepada figur guru ternyata tidak
dengan sendirinya dapat terwujud sebagaimana ketaatan anak kepada figur I dan
II, ayah dan ibunya. Kondisi itu terjadi karena tidak semua orang Madura
mempunyai kesempatan untuk menjadi figur guru. Kendati pun terdapat
anggapan-prediktif bahwa figur guru sangat mungkin diraih oleh murid karena
aspek genealogis namun dalam realitasnya tidak dapat dipastikan bahwa setiap
murid akan menjadi guru, mengikuti jejak orangtuanya. Oleh karenanya, makna
kultural yang dapat ditangkap adalah bahwa bagi orang Madura belum cukup tersedia
ruang dan kesempatan yang leluasa untuk mengubah statusnya menjadi orang yang
senantiasa harus berperilaku patuh, tunduk, dan pasrah.
Kepatuhan
orang Madura kepada figur Rato
(pemimpin pemerintahan) menempati posisi hierarkis keempat. Figur Rato dicapai oleh seseorang ─ dari
mana pun etnik asalnya ─ bukan karena faktor genealogis melainkan karena
keberhasilan prestasi dalam meraih status. Dalam realitasnya, tidak semua orang
Madura diperkirakan mampu atau berkesempatan untuk mencapai posisi sebagai Rato, kecuali 3 atau 4 orang (sebagai
Bupati di Madura) dalam 5 hingga 10 tahun sekali. Itu pun baru terlaksana
ketika diterbitkan kebijakan nasional berupa Undang-Undang tentang Otonomi
Daerah, tahun 1999 yang baru lalu.
Oleh
karena itu, kesempatan untuk menempati figur Rato pun dalam realitas praksisnya merupakan kondisi langka yang
relatif sulit diraih oleh orang Madura. Dalam konteks itulah dapat dinyatakan
bahwa sepanjang hidup orang-orang Madura masih tetap dalam posisi yang
senantiasa harus patuh. Begitulah posisi subordinatif-hegemonik yang menimpa
para individu dalam entitas etnik Madura.
Secara
kultural dapat dimengerti mengapa hierarki Ayah diposisikan lebih tinggi dari
Ibu. Posisi Ayah dalam sosiokultural masyarakat etnik Madura memegang kendali
dan wewenang penuh lembaga keluarga sebagai sosok yang diberi amanah untuk
bertanggung jawab dalam semua kebutuhan rumah tangganya, di antaranya:
pemenuhan keperluan ekonomik, pendidikan,kesehatan, dan keamanan seluruh
anggota keluarga, termasuh di dalamnya Sang Ibu sebagai anggota dalam
“kepemimpinan” lelaki.
Di
sisi lain, kepatuhan kultural orang Madura kepada Guru (Kiai/Ustadz) maupun
kepada pemimpin pemerintahan karena peran dan jasa mereka itu dipan dang
bermanfaat dan bermakna bagi survivalitas entitas etnik Madura. Guru berjasa
dalam mencerahkan pola pikir dan perilaku komunal murid untuk memperoleh
kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan mendiami negeri akhirat kelak.
Kontribusi mereka dipandang sangat bermakna dan berjasa besar karena telah
memberi bekal untuk survivalitas hidup di alam dunia dan keselamatan akhirat
pascakehidupan dunia. Sedangkan pemimpin pemerintahan berjasa dalam mengatur
ketertiban kehidupan publik melalui penyediaan iklim dan kesempatan bekerja,
mengembangkan kesempatan bidang ekonomik, mengakomodasi kebebasan beribadat,
memelihara suasana aman, dan membangun kebersamaan atau keberdayaan secara
partisipatif. Dalam dimensi religiusitas, sebutan figur Rato dalam perspektif etnik Madura dipersamakan dengan istilah ulil amri yang sama-sama wajib untuk
dipatuhi.
Persoalan
yang paling mendasar sesungguhnya terletak pada pemaknaan kultural tentang
kepatuhan dalam konteks subordinasi, hegemoni, eksploitasi, dan berposisi kalah
sepanjang hidup. Pemaknaan tersebut perlu diletakkan dalam posisi yang
berkeadilan dan proporsional. Jika kepatuhan hierarkis kepada figur I dan II
tidak ada masalah karena terbentang luas untuk memperoleh dan mengubahnya
secara siklis maka upaya untak mengubah kepatuhan hierarkis pada figur III dan
IV dapat ditempuh melalui kerja keras dan optimisme disertai bekal pengetahuan
yang sangat memadai. Karenanya, persoalan-persoalan kultural tentang konsepsi
kepatuhan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang tanpa solusi untuk mengubahnya.
A.
Carok
di Madura
Carok
adalah institusionalisasi dalam Masyarakat Madura yang memiliki relasi sangat
kuat dengan faktor-faktor struktur budaya, struktur sosial, kondisi sosial
ekonomi, agama dan pendidikan (Wiyata 2002:231). Carok secara historis telah menjadi bagian dari masyarakat Madura.
Tradisi Carok telah berlangsung sejak
berabad-abad yang lalu. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah maupun pihak yang
berkuasa baik pada masa ini maupun masa lalu tidak berkompeten dalam mengontrol
kekerasan dan juga melindungi masyarakat dari kekerasan yang terjadi. Dalam
budaya Madura Carok selalu dijadikan
sebagai sarana dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Hal ini mencerminkan
bahwa tidak adanya sarana bagi para pelaku Carok
untuk menyelesaikan konflik.
Carok
terjadi disebabkan oleh perasaan terhina atau malo pada diri si pelaku karena harga dirinya dilecehkan oleh orang
lain. Pelecehan harga diri sama dengan pelecehan terhadap kapasitas diri.
Padahal kapasitas diri seseorang secara sosial tidak dapat dipisahkan dengan
peran dan statusnya dalam struktur sosial. Bagi orang Madura tindakan tidak
menghargai dan tidak mengakui atau mengingkari peran dan status sosial sama
artinya dengan memperlakukan dirinya sebagai orang yang tidak mempunyai
eksistensi diri dan pada gilirannya menimbulkan rasa malo. Di lain sisi, apabila seorang laki-laki Madura tidak berani
melakukan Carok maka lingkungan
sekitarnya akan menganggap bahwa dia bukanlah orang Madura yang sesungguhnya
dan sekaligus menjadi bahan cemoohan diantara orng-orang. Jadi, orang Madura
melakukan Carok juga sebagai jalan
agar dia diakui sebagai orang Madura. Oleh karena itu Carok dijadikan sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas
etnisnya.
Cara
untuk melakukan Carok sendiri ada dua
macam. Yang pertama adalah dengan cara ngonggai.
Cara ini dilakukan dengan bentuk menantang secara langsung orang yang akan
diajak Carok. Cara ini biasanya tidak
membutuhkan waktu lama dalam persiapannya. Namun yang dibutuhkan adalah
persiapan mental yang harus dilakukan lebih lama oleh si pelaku. Cara yang
selanjutnya adalah nyekep. Cara ini
dilakukan dengan cara menyimpan senjata dalam baju si pelaku, ketika sudah
bertemu dengan korban maka Carok pun
dilaksanakan. Cara ini membutuhkan persiapan yang lebih lama ketimbang cara
pertama. Hal yang harus dilakukan oleh pelaku adalah mengamati kebiasaan korban
dan mengetahui segala tempat yang biasa didatangi korban. Hal ini minimal
memerlukan persiapan selama satu bulan. Tradisi nyekep sudah sulit untuk ditinggalkan oleh masyarakat Madura.
Setiap saat mereka keluar rumah selalu membawa senjata tajam, lebih-lebih jika
sedang mempunyai musuh.
Persiapan
untuk Carok (baik ngonggai atau nyekep) adalah melakukan pengintaian yang cermat, apalagi terhadap
masalah-masalah yang sensintif. Selain itu biasanya sebelum melakukan Carok pihak pelaku mengadakan sidang
keluarga. Sidang keluarga itu diikuti oleh para tetua dari keluarganya. Hal ini
bertujuan untuk mendapatkan ijin dari pihak keluarga.
Setelah
itu prasyarat selanjutnya adalah tampeng
sereng. Hal ini berbentuk kekuatan supranatural yang dipercaya dapat
menambah kekuatan pelaku Carok. Ada
tiga macam mantera yang digunakan yaitu nylateng,
nyepet dan mesem (Wiyata
2002:192). Nylateng membuat sang
pelaku merasa berani, nyepet membuat
orang menjadi kebal dan mesem membuat
luluh hati musuh (musuh menjadi tidak marah).
Persyaratan
selanjutnya adalah tersedianya dana. Dana tersebut ditujukan untuk
menyelenggarakan ritual keagamaan bagi pelaku Carok yang tebunuh. Misalnya, upacara tahlilan memperingati
kematian dalam jangka waktu 1 minggu, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Kemudian
dana tersebut juga ditujukan untuk melakukan nabang bagi pelaku Carok
yang selamat. Nabang merupakan upaya
keluarga pelaku Carok untuk
merekayasa proses peradilan dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada aparat
agar hukuman pelaku Carok berkurang
atau menjadi ringan. Bahkan apabila pelaku Carok
dua orang, dengan adanya nabang, maka
yang dihukum hanya bisa satu orang saja. Selain itu dana juga dibutuhkan
untuk menyelanggarakan tradisi remo.
Tradisi remo sendiri merupakan suatu acara
hiburan yang para orang jago atau blater
berkumpul dalam sebuah pesta yang biasanya menampilkan hiburan seperti ludruk. Pelaksanaannya sama seperti
arisan yaitu para anggotanya wajib membayar uang kepada penyelenggara.
Referensi:
Taufiqurrahman. “Islam dan Budaya Madura.” www.ditpertais.net/ancon06/Makalah%20Taufiqurrahman..doc (24 Januari 2012)
Wiyata, A. Latief. Carok; Konflik Kekerasan dan Harga
Diri Orang Madura. Yogyakarta: LkiS, 2002.
Wiyata,
A. Latief. Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura.
Jakarta: CERIC-FISIP UI, 2003.
Sabtu, 12 Januari 2013
Refleksi Kampus : Danau UI
Pemanfaatan Danau UI :
Antara Aksesbilitas, Kerusakan
Lingkungan dan Penyelamatan Kolaboratif
Pendahuluan
Degradasi
atau penurunan kualitas lingkungan hidup, banyak ditemui pada kota-kota besar termasuk
di Kota Depok[1]. Kota
Depok merupakan kota dengan dataran landai dengan
rata-rata ketinggian 121 meter dari permukaan laut, dan dikelilingi oleh
kota-kota besar seperti Kota Bogor dan Kota Jakarta. Letaknya yang dekat dengan
Kota Jakarta, menjadikan Kota Depok menjadi daerah penyangga bagi Kota Jakarta.
Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang No. 15 Tahun 1999 yang menetapkan Kota
Depok yang memiliki luas 20.209 hektare sebagai daerah penyangga bagi Kota
Jakarta[2]. “Gelar” daerah penyangga
yang dipegang oleh Kota Depok, salah satunya bermakna bahwa Kota Depok memiliki
fungsi menjadi daerah resapan air bagi Kota Jakarta. Selain sebagai daerah
resapan air bagi Kota Jakarta, jika mengingat letaknya yang secara geografis
diantara Kota Jakarta dan Kota Bogor, Kota Depok juga dapat berfungsi lebih,
yakni mengelola curahan air dari Kota Bogor yang mengalir menuju Kota Jakarta.
“Gelar” daerah penyangga yang dipegang Kota Depok, hendaknya harus segara
dikaji dan dikelola lebih baik lagi, karena fungsinya yang sudah mulai luntur.
Letak Kota Depok yang begitu strategis,
yakni dekat dengan Kota Jakarta membuat perkembangan Kota Depok berkembang
begitu pesat. Perkembangan Kota Depok tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu
imbas berkembangnya Kota Jakarta. Sebagai imbas dari berkembangnya Kota Jakarta akibatnya, meningkatkan kebutuhan akan ruang usaha dan kepentingan publik
dan juga berdampak pada
menyempitnya lahan tempat tinggal. Ditambah lagi belum berhasilnya pemerintah
terhadap program penanganan urbanisasi sehingga melengkapi memburuknya
kebutuhan akan ruang tempat tinggal. Kondisi ini tentu membebani kawasan
marjinal kota (sub urban), seperti Kota Depok, yang akhirnya menjadi kawasan penyedia lahan[3].
Selain masalah keterbatasan ruang, perkembangan Kota Depok yang
begitu pesat juga tidak diiringi dengan pembangunan yang ramah lingkungan, hingga akhirnya
daerah-daerah resapan air di Kota Depok lambat laun menjadi berkurang.
Berkurangnya daerah resapan air yang secara signifikan berkurang adalah daerah
danau, baik itu danau buatan atau danau alami. Dari data yang berhasil saya
himpun, dari sekitar 30 danau yang terdapat di Kota Depok, ternyata 28 danau
dinyatakan dalam keadaan rusak berat atau kritis. Bahkan 5 dari 30 danau yang
ada, sudah tidak berfungsi sama sekali.[4] Berkurangnya daerah
resapan air khususnya danau di Kota Depok sudah sangat memprihatinkan, dan
berimplikasi pada keharusan seluruh elemen masyarakat Kota Depok untuk turut
serta dalam melakukan pengelolaan danau yang ada. Salah satu elemen masyarakat
Kota depok yang memiliki peran penting dalam pengelolaan danau adalah
Universitas Indonesia. Universitas
Indonesia, memiliki 6 buah danau yang 5 diantaranya merupakan danau buatan[5]. Idealnya sesuai peraturan
yang berlaku ( SK Rektor UI Tahun 2007 mengenai Pembinaan Lingkungan Kampus), danau UI hanya diperuntukan fungsinya sebagai
daerah edukasi, rekreasi, dan daerah resapan air. Namun, pada kenyataannya
banyak masyarakat yang mengambil manfaat lebih dari danau UI diluar peruntukan
yang semestinya. Fenomena ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut,
untuk melihat bagaimana bentuk akses
masyarakat terhadap danau UI, dampaknya yang dihasilkan serta kerusakan yang
ditimbulkan dan bagaimanakah pola-pola penyelamatan danau UI, sebagai salah
satu “situs” ekologis perkotaan.
Danau UI : Sebuah
Gambaran Ekologis
Universitas Indonesia merupakan sebuah
lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah dan
mempunyai fasilitas-fasilitas penting di dalamnya. Universitas Indonesia
berdiri pada tahun 1849 dan merupakan institusi atau lembaga pendidikan dengan
sejarah paling tua di Asia.[6]
Secara geografis, lokasi kampus UI berada di dua area yang
cukup berjauhan, yakni kampus Salemba dan kampus Depok. Kampus Depok memiliki
luas lahan mencapai 320 hektar dan mayoritas fakultas UI berada di Depok,
dengan atmosfer green kampus karena
25% lahan hanya digunakan sebagai sarana akademik dan non akademik, selebihnya
75% lahan UI bisa dikatakan sebagai area hijau berwujud hutan kota yang
mencirikan ekosistem hutan tropis dengan tiga bentuk ekosistem unggulan yaitu :
ekosistem pepohonan yang bersumber dari Indonesia bagian timur, ekosistem pepohonan wilayah Indonesia bagian barat, dan komplek vegetasi asli JABODETABEK yang dipadu
serasi dengan daerah hutan jati mas yang tumbuh hijau diantara gedung Rektorat UI, FASILKOM,
serta FISIP UI.[7]
Kampus UI Depok, secara teritorial berdiri diatas 2 wilayah administratif yang
berbeda. Kampus UI Depok bagian utara (danau salam - danau puspa), masuk dalam
wilayah administratif kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan
kampus UI bagian selatan (danau ulin – danau aghatis), masuk dalam wilayah
administratif Kota Depok, Jawa Barat.
Danau UI adalah danau yang
berada di lingkungan kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Enam Danau yang berlokasi di daerah UI tersebut
memiliki nama yaitu, Kenanga, Aghatis, Mahoni, Puspa, Ulin, Salam, dan jika
nama dari masing-masing danau di UI tersebut di ambil huruf depannya, maka akan
membentuk satu yakni KAMPUS. Setiap
danau, diberi nama sesuai dengan nama-nama pohon yang dahulu banyak tumbuh di
wilayah kampus UI. Danau UI masuk dalam jenis danau“Eutropik” sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan
makanan, karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya adalah airnya
keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen terdapat di daerah
profundal.[8]
Adapun lokasi-lokasi dari
keenam danau tersebut yaitu :
1.
Danau kenanga berlokasi di antara Gedung Rektorat Balairung dan Masjid UI yang dibangun tahun 1992 dengan
luas 28.000 m2 . Danau kenanga
sebenarnya adalah danau semi buatan. Dahulu danau kenanga merupakan daerah rawa
yang dangkal, yang kemudian dibentuk dan digali kembali hingga berbentuk
seperti sekarang.
2.
Danau Agathis berlokasi di antara FMIPA dan
Politeknik Negeri Jakarta, dibangun tahun 1995 dengan luas 20.000 m2.
3.
Danau Mahoni terletak di sebelah Utara dan Selatan Kampus yang dibatasi
oleh jalan utama lingkar selatan (sebelah timur FIB dan PSJ, serta
sebelah Barat FE), dibangun pada tahun 1996 dengan luas 45.000 m2 .
4.
Danau Puspa terletak antara Danau Ulin dan Danau Mahoni, dibangun pada
tahun 1995 dengan luas 20.000 m2 .
5.
Danau Ulin berlokasi diantara Danau Puspa dan Danau Salam dan dibangun pada
tahun 1998 dengan luas 72.000 m2 .
6. Danau Salam, yang
berlokasi bersejajar sesuai aliran dari selatan ke utara
sebagai bagian rangkaian Danau Ulin dan Danau Puspa, yang dibangun pada tahun
1998 dengan luas 42.000 m2.[9]
Pemanfaatan Danau :
Antara Aksesbilitas dan Dampak Ekologis
Mengacu
pada pola pikir teori akses (Ribot, J.C., & N.L. Peluso 2003)[10],
danau UI saya kategorikan sebagai sebuah sumber daya properti bagi Universitas Indonesia.
Pengkategorian sebagai sumber daya properti dikarenakan danau UI merupakan hak
milik Universitas Indonesia, yang didasarkan atas klaim, konvensi atau kekuatan
hukum yang ada. Pemanfaatan dan pengelolaan danau UI secara properti tunduk dan
patuh pada aturan pengelolaan para pengelola kampus UI. Saya melihat bahwa
danau-danau di kampus UI pada satu sisi memang merupakan sebuah sumber daya
properti, karena berdasarkan hak yang disandarkan pada klaim dan hukum yang
ada. Namun disisi lain, saya juga melihat bahwa danau UI tidak hanya dapat
disebut sebagai sebuah sumber daya properti, namun juga dapat disebut sebagai
sebuah akses. Dalam teorinya, Ribot J.C., & N.L. Peluso, mendefinisikan
akses sebagai sebuah kemampuan mengambil manfaat dari hal-hal termasuk objek
material, orang, lembaga dan simbol-simbol. Dengan fokus pada kemampuan
mengambil manfaat dari sebuah objek material atau sumber daya, saya melihat
bahwa danau UI adalah sumber daya yang dapat diambil manfaatnya oleh seluruh
masyarakat sekitar UI, dan seluruh masyarakat itu sendiri memiliki kemampuan
untuk mengambil manfaatnya secara langsung atau tidak langsung. Bentuk akses
akan sumber daya demikianlah yang saya sebut sebagai open access.
Selain
menganalisis bahwa danau UI merupakan sebuah open access, saya juga menganalisis bagaimanakah bentuk-bentuk
pemanfaatan dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari bentuk pemanfaatan danau UI
sebagai sebuah open access.
Pemanfaatan-pemanfaatan tersebut saya menganalisisnya dengan konsep teori akses
dan membaginya berdasarkan 2 macam jenis
mekanisme akses, yakni legal access dan ilegal access.
Legal access intinya adalah
hak yang didefinisikan oleh hukum,
aturan, atau konvensi yang membentuk kontrol dan pengelolaan terhadap akses.
Kepemilikan berdasar-hukum mencakup akses lewat memegang hak milik dengan izin
dan lisensi dimana pemegangnya dapat mengendalikan akses. Orang lain yang tidak
memilikinya harus datang pada pemegang izin dan lisensi tersebut untuk
memperoleh atau mengelola akses. Sedangkan ilegal
access adalah pemanfaatan yang mengarah pada kesenangan mengambil manfaat
dari sesuatu dengan cara yang secara sosial tidak dikenakan sanksi oleh negara
atau pihak yang berwenang. Bentuk-bentuk pemanfaatanya antara lain :
1. legal access
Pemanfaatan
dengan mekanisme legal access pada danau UI, secara singkat dapat diartikan
sebagai pemanfaatan danau UI berdasarkan peraturan yang ada. Peraturan yang
menyangkut mengenai pemanfaatan dan pengelolaan danau UI yakni SK Rektor UI
mengenai Pembinaan Lingkungan Kampus (PLK) tahun, 2007. Peraturan tersebut
mengamanatkan pemanfaatan danau-danau di wilayah kampus UI, difungsikan sebagai
sarana-sarana seperti dibawah ini :
- Pemanfaatan
Danau UI Sebagai Sarana Edukasi
Danau
UI dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, dalam arti danau UI dijadikan sebagai
sarana penunjang bagi para civitas akademika Universitas Indonesia dalam melakukan
riset, atau penelitian.
b. Sebagai
Sarana Rekreasi
Relaks
dan bersantai merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia yang bernilai
positif[11].
Kebutuhan manusia akan rileks dan bersantai salah satunya dipenuhi dengan cara
rekreasi. Rekreasi yang dilakukan bertujuan untuk melepaskan penat dan stres
akan rutinitas, atau masalah-masalah yang sedang dihadapi. Salah satu media
rekreasi adalah dengan cara berkunjung ke tempat-tempat yang dianggap memiliki
nilai keindahan atau dapat menenangkan dan menyenangkan perasaan. Danau UI
(khususnya danau Salam dan danau Kenanga), kerap kali dikunjungi baik oleh
civitas akademika UI, atau masyarakat sekitar UI untuk berekreasi.
c.
Sebagai Daerah Resapan Air
Danau UI sebagai daerah resapan air,
jika melihat dari perspektif secara fungsional dapat dikatakan bahwa inilah
fungsi danau UI yang utama. Menurut penjabaran Kepress RI No.32 Tahun 1990,
tentang pengelolaan kawasan lindung, danau berfungsi sebagai daerah resapan
air, pengendali banjir, dan menjaga ketersediaan air tanah. Fungsi ini sangat
penting bagi Kota Jakarta dan Depok secara umum, dan bagi kampus UI secara
khusus. Jika danau tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengakibatkan banjir,
atau musibah kekeringan yang dikarenakan hilangnya ketersediaan air tanah.
2.
Ilegal access
Pemanfaatan
danau UI dengan mekanisme ilegal access,
secara singkat dapat diartikan sebagai pemanfaatan danau UI diluar peraturan
yang telah ditentukan. Pemanfaatan dengan mekanisme ilegal access, mengarah pada kesenangan mengambil manfaat dari
sesuatu dengan cara yang secara sosial tidak dikenakan sanksi oleh negara atau
pihak yang berwenang. Ilegal access banyak
dilakukan dengan cara “negoisasi” peraturan dengan cara melakukan lobi pada
aparat, atas dasar hubungan sosial (pertemanan) dan pemakluman keadaan.
Beberapa bentuk pemanfaatan dengan mekanisme ilegal access antara lain :
a. Kegiatan Memancing
Ikan
.
Kegiatan memancing ikan, walaupun dianggap sebagai kegiatan yang ilegal dan
dilarang untuk dilakukan namun kegiatan tersebut masih tetap ”marak” dilakukan
oleh masyarakat.
b
. Kegiatan Menjala Ikan
Kegiatan
menjala ikan, memang merupakan kegiatan yang tidak sepopuler kegiatan
memancing. Para penjala, menjala ikan dengan menggunakan rakit dan jala. Rakit yang digunakan tergolong sederhana,
karena terbuat dari susunan bambu yang diikat yang ditambah dengan susunan ban
bekas yang dipasang diujung rakit. Jala yang digunakan, juga tergolong biasa
seperti jala yang digunakan untuk menjala ikan pada umumnya.
c.
Berjualan
Salah
satu kegiatan yang merupakan akses yang ilegal dalam memanfaatkan danau UI
adalah berjualan. Kegiatan berjualan yang biasa masyarakat lakukan adalah
dengan cara menjajakan minuman seperti kopi atau teh manis, dan juga makanan
ringan seperti roti atau gorengan. Jika dianalisis lebih lanjut, kegiatan
berjualan di danau UI sebenarnya merupakan efek turunan dari bentuk-bentuk
akses terhadap danau UI yang lainnya. Kehadiran orang-orang yang berjualan,
hadir dikarenakan banyaknya orang yang ada untuk memanfaatkan danau UI. Para
pedagang merasa kehadiran orang-orang yang memanfaatkan danau UI sebagai sebuah
peluang untuk menjajakan dagangannya.
d.
Kegiatan Membuang Sampah
Kegiatan membuang sampah menurut
pengamatan saya merupakan kegiatan yang paling merusak yang dilakukan dalam
kerangka mekanisme ilegal access.
Kegiatan membuang sampah pada danau UI dilakukan oleh masyarakat dengan dua
cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan data yang saya himpun, diketahui bahwa sampah
yang ada di danau UI khususnya di danau Puspa merupakan hasil pembuangan sampah
yang dilakukan secara tidak langsung. Sampah-sampah tersebut berasal dari pasar
Kemiri Muka, Depok dan masuk ke danau UI karena dibawa oleh arus melewati
gorong-gorong air. Sedangkan sampah yang yang secara langsung dibuang,
didominasi oleh sampah yang dibuang oleh para civitas akademika itu sendiri,
dan sampah hasil sisa para pedagang sekitar danau UI.
Setelah
membahas mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan yang dilakukan, selanjtnya saya
akan menjelaskan dampak-dampak apa sajakah yang dtimbulkan dari
pemanfaatan-pemanfaatan tersebut. Dampak-dampak tersebut antara lain :
a.
Dampak Positif
Danau
UI berdampak secara ekonomi pada masyarakat sekitar kampus UI. Berdasarkan
hasil pengamatan, danau UI menjadi salah satu sarana mencari nafkah baik secara
langsung maupun tidak langsung pada pemanfaatnya.
b.
Dampak Negatif
Dampak
negatif dari pemanfaatan danau UI adalah kerusakan pada lingkungan
danau itu sendiri . Kerusakan tersebut, banyak didominasi karena pembuangan sampah yang sembarangan
baik secara langsung atau tidak langsung. Pemancingan ikan dan pengambilan ikan
dengan menjalanya secara terus menerus juga mengambil andil dalam kerusakan
lingkungan danau. Pemancingan dan penjalaan ikan yang terus menerus, dapat mengganggu keseimbangan
ekosistem danau itu sendiri. Sedangkan sampah yang menumpuk, dapat menjadi
polutan yang merusak ekosistem danau, mengganggu keseimbangan daerah resapan
air, bahkan dapat menjadi sarang berkembangnya penyakit. Pada akhirnya,
kerusakan lingkungan danau UI itu sendiri akan berdampak pada manusia
disekitarnya, baik dalam bentuk bencana alam (banjir atau kekeringan), atau
wabah penyakit.
Kerusakan
Danau UI : Sebuah Bentuk Politics Of Unsustainability
Kerusakan
pada danau UI, sebagai konsekuensi dari aksesbilitasnya dapat kita lihat
sebagai sebuah kerusakan yang mayoritas dilakukan oleh manusia. Masalah pembuangan sampah (baik langsung maupun tidak
langsung) yang dilakukan tanpa adanya regulasi yang tepat dan bertanggungjawab
dinilai sebagai salah satu penyebab terbesar dari kerusakan danau UI. Ketidakjelasn
regulasi yang tepat dan bertanggungjawab inilah daerah yang kemudian
menyebabkan apa yang disebut sebagai Politics Of Unsustainability[12]. Politics Of
Unsustainability, didefiniskan oleh Shoreman, Elanor E., & Nore
Haenn (2009), dalam tulisannya “Regulation, Conservation, and Collaboration
: Ecological Anthropology in the Mississippi Delta” sebagai sebuah keadaan non ekologis (sosial, politik, hukum,
ekonomi, kultural ) yang buruk yang juga menyebabkan buruknya keadaan ekologis
(lingkungan primer, alam). Keadaan Non ekologis yang buruk dalam hal ini saya
melihatnya dalam bidang hukum atau aturan yang tidak jelas dalam penanganan
sampah di danau UI.
Seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya, sampah yang beredar di danau UI mayoritas
merupakan sampah yang bukan berasal dari sekitaran danau UI. Jika kita
mengamati lebih mendalam, sampah-sampah yang banyak bertebaran merupakan
sampah-sampah pasar yang berasal dari pasar kemiri muka, Depok. Sampah-sampah
tersebut dibuang ke gorong-gorong yang kemudian hanyut dan terbawa (atau
sengaja diarahkan), ke danau UI.
Yang
menjadi persoalan besar adalah, kemudian tidak adanya tindakan penyelesaian
yang berkelanjutan dari pemerintah kota Depok untuk menyelesaikan masalah
tersebut. Padahal jika kita mengacu kembali pada aturan UU No. 15 Tahun 1999 tentang kota Depok sebagai daerah penyangga
(khususnya dalam hal ekologis daerah ibukota Jakarta), harusnya ini menjadi salah
satu poin dan perhatian khusus yang dilakukan oleh pemerintah kota. Setali tiga
uang dengan pemerintah Depok, solusi-solusi yang dilakukan oleh kampus UI tidak
kalah “acak adutnya”. Beberapa kali penyelesaian atas kerusakan danau UI hanya
dilakukan dengan tindakan-tindakan yang temporal bahkan seremonial semata namun
tidak menyelesaikan akar dari permasalahan tersebut secara utuh. Salah satu pengalaman
dari tindakan penyelamatan seremonial yang pernah saya saksikan adalah ketika
penyelamatan danau UI di awal tahun 2012. Ketika itu pihak rektorat UI dibantu
oleh departemen lingkungan BEM UI dan departemen sosial kemasyarakatan se-UI
mengadakan sebuah acara pembersihan danau UI (tepatnya di danau puspa) dengan
tajuk #SaveDanauUI.
Kegiatan ini
menurut saya merupakan kegiatan yang besar namun cukup sia-sia. Bagiamana
tidak, dengan jumlah peserta yang cukup banyak namanun tidak memberikan dampak
yang signifikan dan berkelanjutan. Hasilnya secara singkat bisa dirasakan,
namun seminggu kemudian danau yang sudah dibersihkan menjadi kotor kembali
karena sampah. Solusi-solusi yang harus dilakukan kemudian harusnya merupakan
solusi yang berkelanjutan dan kolaboratif untuk menjawab permasalahan secara
utuh.
Penyelamatan
Kolaboratif : Solusi Berkelanjutan Penyelamatan Danau UI
Masalah
pembuangan sampah ditambah dengan Politics Of
Unsustainability dalam dimensi aturan atau hukum , sudah seharusnya
mendapatkan solusi yang tepat dalam penyelesainnya. Solusi yang tepat ini pula
diharapkan bukan hanya menjawab permasalahan secara secara parsial dan temporal
namun dapat menjawab secara holistik
dan berkelanjutan. Salah satu, solusi penyelamatan yang holisitk dan berkelanjutan yang saya nilai tepat untuk
menyelamatkan danau UI adalah dengan cara penyelamatan kolaboratif.
Penyelamatan
kolaboratif, menurut Peraturan Menteri Kehutanan P.19/2004
merupakan sebuah tindakan penyelamatan dengan mempertimbangkan keterlibatan
dari banyak pihak yang memiliki kepentingan atas sebuah objek atau sumber daya
tersebut. Lain halnya dengan apa yang dijelaskan oleh Moseley, C. (2003[13]). Menurutnya, pendekatan penyelamatan
kolaboratif merupakan proses dimana pihak yang berlatar belakang plural
berunding dan bereskperimen untuk mendefinisikan prioritas, mengembangkan
solusi termasuk hubungan masing-masing pihak terhadap pengelolaan sumber daya
alam. Mengikuti pola pikir dari Moseley kemudian, hal pertama yang kita lakukan
dalam penyelamatan kolaboratif adalah mendefinisikan prioritas pihak-pihak yang
berkepentingan, atau kemudian yang disebut sebagai analisis pemangku
kepentingan.
Dalam
analisis pemangku kepentingan, perlu dipetakan kemudian
kepentingan-kepentingan, solusi dan hambatan apa sajakah yang ada dilapangan. Mapping dalam analisis pemangku
kepentingan ini pula penting halnya khususnya dalam menghindari konflik dalam
usaha penyelamatan danau UI . Setelah melakukan analisis kepentingan
pihak-pihak yang terkait, perlu adanya intensi lebih untuk mengkomunikasikan
solusi dan pola penyelamatan yang bagaimanakah yang harus dilakukan untuk
menyelamatkan danau UI.
Proses
komunikasi yang dilakukan perlu memberikan sebuah hasil belajar yang dapat
memberikan solusi yang kolaboratif dan berkelanjutan terhadap pemecahan kerusakan
danau UI. Secara umum, saya mengusulkan proses komunikasi pihak-pihak yang
terkait seperti skema di bawah ini :
Setelah melakukan proses analisis kepentingan,
lalu melakukan proses komunikasi yang melibatkan partisipasi dan proses belajar
didalamnya, langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam sebuah penyelamatan
kolaboratif menurut Moseley adalah melakukan evaluasi pelaksanaan yang kemudian
dijadikan bahan dalam melihat faktor pendukung dan penghambat dalam proses
penyelamatan kolaboratif tersebut, sehingga tercipta sebuah solusi yang bukan
hanya bersifat holistik namun juga
bersifat berkelanjutan.
Kesimpulan
Pemanfaatan-pemanfaatn yang dilakukan oleh
masyarakat sekitar kampus UI memiliki dampak baik dampak yang positif, maupun
dampak yang negatif. Dampak pemanfaatan yang positif dilahirkan dari
pemanfaatan danau yang bertanggung jawab yang berkomitmen pada aturan dan
mengacu pada pemanfaatan danau yang ramah lingkungan dan cenderung konservatif.
Sedangkan dampak pemanfaatan danau yang negatif, dilahirkan dari pemanfaatan
danau yang tidak bertanggung jawab, tidak ramah lingkungan dan cenderung
eksploitatif. Pada masalah
kerusakan danau UI hendaknya diselesaikan dengan pola penyelamatan yang holistik dan berkelanjutan, yakni dengan
penyelamatan kolaboratif. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam
penyelamatan kolaboratif antara lain (1) Analisis pemangku kepentingan (2)
menciptakan proses belajar komunikasi dan partisipasi dalam rangka penyelamatan
(3) Melakukan evaluasi terhadap faktor penghambat dan pendukung proses
penyelamatan yang kolaboratif.
Terakhir, dalam melakukan
pemanfaatan lingkungan hendaknya dilakukan dengan arif dan bijak, dengan selalu
mengingat bahwa alam bukanlah sumber daya yang diwariskan oleh nenek moyang
yang dapat dimanfaatkan dengan seenaknya, melainkan alam adalah warisan anak
cucu yang harus dijaga dan dipelihara.
Daftar
Pustaka
Koentjaraningrat.1979. Pengantar Antropologi. Jakarta : Rineka
Cipta.
Moseley,
C. 2003. “Constrained Democracy: Environmental Outcomes and Collaborative
Management.” Paper presented at the conference entitled, Evaluating Methods
and Environmental Outcomes of Community-Based Collaborative Processes, Salt
Lake City, September 14-16, 2003.
Ribot, J.C., & N.L.
Peluso 2003 “A Theory of Access”, dalam Rural Sociology 68/2 : 153-170.
Shoreman, Eleanor. “Regulation, Collaboration, and
Conservation: Ecological Anthropology in the Mississippi Delta” Human Ecology.
37 (2009): 90-107.
Referensi
Internet :
http://www.anakui.com/2009/07/27/sejarah-danau-ui-between-legend-n-myth/
(25
Desember 2012 -11.30 WIB)
http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-5114-3106100603-bab1.pdf
( 25 Desember 2012-14.30 WIB)
http://indonesiahijau.or.id
(25 Desember 2012-12.30 WIB)
http://indonesiahijau.or.id
(25 Desember 2012-12.33 WIB)
http://www.ui.ac.id/id/ (25 Desember 2012-14.30 WIB)
[3] Dikutip dari : http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-5114-3106100603-bab1.pdf
( 25 Desember 2012-14.30 WIB)
[8] Dikutip dari http://www.anakui.com/2009/07/27/sejarah-danau-ui-between-legend-n-myth/(25
Desember 2012 -11.30 WIB)
[10]
Diintisari dari : Ribot, J.C., & N.L. Peluso 2003 “A Theory of Access”,
dalam Rural Sociology 68/2 : 153-170.
[12]
Diintisari dari : Shoreman, Eleanor. “Regulation, Collaboration,
and Conservation: Ecological Anthropology in the Mississippi Delta” Human
Ecology. 37 (2009): 90-107.
[13]
Moseley, C.
2003. “Constrained Democracy: Environmental Outcomes and Collaborative
Management.” Paper presented at the conference entitled, Evaluating Methods
and Environmental Outcomes of Community-Based Collaborative Processes, Salt
Lake City, September 14-16, 2003.
Langganan:
Komentar (Atom)